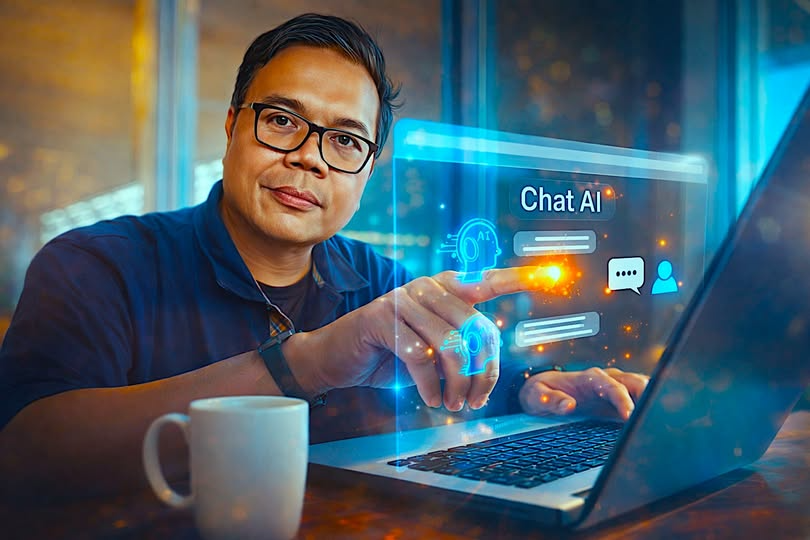STASIUN-STASIUN JIWA: KETIKA PUISI MENJADI RUMAH BAGI TUBUH, BUMI, DAN KENANGAN
Catatan untuk Buku Kumpulan Puisi “Stasiun Rupa Aksara”
karya Erna Winarsih Wiyono
oleh: Riri Satria
PENDAHULUAN
Ada buku puisi yang kita baca seperti menikmati karya sastra dari kejauhan, mengagumi metaforanya, mengukur tekniknya, lalu menutupnya dengan kesan intelektual yang rapi. Namun ada juga buku puisi yang kita baca seperti kita sedang duduk di samping seseorang di ruang tunggu kehidupan, mendengar napasnya, jeda suaranya, getar yang tidak selalu terlihat. “Stasiun Rupa Aksara” karya Erna Winarsih Wiyono terasa seperti yang kedua. Ia bukan sekadar teks, melainkan ruang singgah batin. Setidaknya itu menurut saya.
Saya memang memberikan prolog untuk buku kumpulan puisi karya Erna ini, namun pada tulisan ini saya akan membahasnya dari sudut pandang yang bebeda dengan tulisan para prolog tersebut.
Sejak awal sangat terlihat bahwa Erna dalam buku tidak memiliki ambisi estetik yang ingin memamerkan kepiawaian bahasa puitik, melainkan kebutuhan untuk menulis agar tetap “hidup dari dalam”. Puisi-puisi di dalamnya seperti catatan denyut nadi, ada saatnya stabil, ada saatnya melemah, ada kalanya bergetar pelan memanggil Tuhan, dan di lain waktu memandang bumi dengan mata yang hampir basah.
Membaca buku ini saya merasa seperti sedang berada di sebuah stasiun kecil pada sore hari, memandangi kereta pengalaman datang dan pergi, sakit, cinta, kehilangan, perjalanan, perempuan, dan semesta yang terus bernafas meski tersengal.
Dalam psikologi seni ada gagasan bahwa menulis bisa menjadi bentuk terapi, semacam ruang aman untuk menata ulang luka dan pengalaman yang terlalu berat ditanggung sendiri. Puisi-puisi dalam buku ini terasa dekat dengan fungsi itu. Ia tidak lahir dari menara gading, tetapi dari ruang rawat batin. Latar belakang hidup penulis memperkuat kesan ini. Sejak kecil sudah akrab dengan dunia tulis-menulis, terpicu oleh bacaan masa kanak-kanak, lalu diperkenalkan pada seni rupa oleh ibunya, ia tumbuh dalam persilangan aksara dan visual.
Pengalaman mengikuti pertukaran budaya, perjalanan dengan ransel, keterlibatan di komunitas sastra dan seni, hingga fase-fase sakit dan pergulatan personal, membuat menulis bagi dirinya bukan sekadar kegiatan kreatif, melainkan cara bernapas kedua.
KERANGKA PSIKOLOGI SENI DAN TERAPI MENULIS
Gagasan bahwa seni, termasuk menulis puisi, dapat menjadi proses penyembuhan berakar pada pemikiran Sigmund Freud tentang sublimasi, yakni penyaluran dorongan batin yang sulit diterima menjadi bentuk kultural seperti karya seni. Dalam perkembangan berikutnya, Carl Gustav Jung melihat ekspresi simbolik sebagai jalan dialog antara kesadaran dan ketidaksadaran.
Lebih spesifik, praktik expressive writing dipopulerkan oleh psikolog James W. Pennebaker, yang menunjukkan bahwa menuliskan pengalaman emosional membantu individu mengolah trauma dan meningkatkan kesehatan psikologis. Dalam konteks inilah puisi-puisi Erna dapat dipahami sebagai proses regulasi emosi dan rekonstruksi makna diri.
Ketika seseorang menulis dari titik-titik genting hidup, bahasa sering kali menjadi jembatan antara rasa yang tak terkatakan dan dunia luar. Dalam teori trauma writing, bahasa membantu memberi bentuk pada yang semula hanya berupa kabut di dada. Itulah yang terasa di sini. Luka tidak disembunyikan di balik simbol-simbol yang terlalu rumit, tetapi dibiarkan berbicara dengan kejujuran yang nyaris telanjang. Sebagai pembaca, saya sering merasa seperti menyentuh permukaan air yang tampak tenang, tetapi tahu di bawahnya ada kedalaman yang dingin dan sunyi. Sedikit banyaknya, itulah Erna yang sudah saya kenal sejak sekitar 10 tahun yang lalu.
TEORI TRAUMA DAN NARASI
Konsep trauma writing banyak dikembangkan oleh teoretikus seperti Cathy Caruth, yang memandang trauma sebagai pengalaman yang awalnya tak terbahasakan dan baru hadir kembali melalui narasi. Sementara Dori Laub menekankan pentingnya kesaksian (testimony) sebagai proses pemulihan. Puisi, dalam konteks ini, berfungsi sebagai ruang kesaksian personal di mana bahasa menjadi cara menghadirkan kembali pengalaman yang semula terfragmentasi.
Judul “Stasiun Rupa Aksara” sendiri sudah membuka pintu tafsir yang luas. Stasiun adalah tempat singgah, bukan tujuan akhir. Dalam hidup, kita jarang benar-benar tiba, kita lebih sering berhenti sejenak, menata napas, lalu melanjutkan perjalanan.
Puisi-puisi di buku ini bekerja seperti stasiun-stasiun pengalaman. Ada stasiun tubuh ketika rasa sakit, usia, dan pengalaman perempuan berbicara. Ada stasiun cinta dengan rindu, pertemuan, dan jarak yang tak selalu bisa dijembatani. Ada stasiun bumi dengan laut, hutan, polusi, bencana, dan alam yang perlahan kelelahan. Ada pula stasiun spiritual tempat doa dan sunyi bertemu dalam sepertiga malam.
PENDEKATAN EKOKRITIK
Pendekatan ekokritik dalam sastra berkembang melalui pemikiran Cheryll Glotfelty dan Lawrence Buell, yang melihat karya sastra sebagai ruang refleksi hubungan manusia dengan alam. Buell menekankan bahwa teks ekokritik menghadirkan alam bukan sekadar latar, tetapi entitas yang memiliki nilai intrinsik. Cara Erna memanusiakan bumi dengan memberinya napas, paru-paru, dan rasa sakit, sangat sejalan dengan paradigma ini.
Salah satu arus paling kuat dalam buku ini adalah relasi manusia dengan bumi. Dalam pendekatan ekokritik, sastra dilihat sebagai cara manusia memahami hubungannya dengan alam. Ada yang menarik menurut saya, di mana alam dalam puisi-puisi ini tidak tampil sebagai pemandangan indah yang jauh, melainkan sebagai tubuh yang ikut menderita. Bumi digambarkan seolah memiliki paru-paru, jantung, napas. Krisis lingkungan terasa seperti kondisi medis darurat. Cara ini membuat kita tak lagi melihat kerusakan alam sebagai data, melainkan sebagai luka makhluk hidup.
Ada empati ekologis yang lembut di sana. Penyair tidak berdiri di luar alam sebagai pengamat, tetapi menjadi bagian dari tubuh yang sama. Saya pribadi merasakan kesedihan ketika membaca gambaran laut yang tercemar atau bumi yang kelelahan. Ada rasa bersalah kolektif yang mengendap, tetapi tidak disampaikan dengan amarah, melainkan dengan nada memohon. Seolah penyair berkata bahwa kita sudah terlalu jauh menyakiti, mari pelan-pelan belajar merawat lagi.
ÉCRITURE FÉMININE DAN TUBUH PEREMPUAN
Selain bumi, tubuh perempuan menjadi ruang penting dalam buku ini. Dalam teori écriture féminine, perempuan menulis dengan tubuhnya, dengan pengalaman biologis, emosional, dan sosial yang khas. Puisi-puisi tentang perempuan di sini terasa sangat personal. Perempuan hadir bukan sebagai simbol romantik, melainkan sebagai tubuh yang mengalami perubahan usia, luka batin, tekanan sosial, sekaligus kekuatan untuk bertahan. Feminisme yang terasa bukan berupa teriakan slogan, melainkan kesadaran diri yang tenang. Seperti perempuan yang sudah terlalu banyak melalui badai, sehingga suaranya justru menjadi lebih lembut, tetapi dalam.
Konsep écriture féminine diperkenalkan oleh filsuf dan kritikus Prancis Hélène Cixous lewat esainya “The Laugh of the Medusa”. Ia menekankan bahwa pengalaman tubuh perempuan melahirkan cara menulis yang berbeda dari struktur patriarkal bahasa. Gagasan ini juga diperkaya oleh Luce Irigaray dan Julia Kristeva, yang melihat bahasa sebagai ruang di mana identitas perempuan dapat dinegosiasikan ulang.
Saya merasakan empati ketika membaca bagian-bagian itu. Seolah penyair tidak sedang berkhotbah, melainkan duduk bersama perempuan lain, berbagi secangkir teh, berbagi cerita tentang tubuh, tentang waktu, tentang bagaimana tetap berdiri meski dunia tidak selalu ramah.
Latar belakang penulis sebagai perupa juga sangat terasa. Imaji-imaji dalam puisinya visual, konkret, seperti lukisan kecil yang digores cepat tetapi tepat. Dalam teori intermedialitas, terjadi perjumpaan antara kata dan rupa. Puisi-puisi ini bukan hanya bunyi, tetapi gambar. Dan gambar itu sering sangat sederhana berupa jendela, laut, daun, rel, cangkir. Kesederhanaan ini justru membuat pembaca mudah masuk. Saya membayangkan setiap puisi seperti sketsa cat air, tidak terlalu detail, tetapi meninggalkan bekas rasa yang lama mengendap.
INTERMEDIALITAS: PERTEMUAN KATA DAN RUPA
Konsep intermedialitas dibahas oleh Irina O. Rajewsky dan Werner Wolf, yang melihat adanya dialog antar medium seni. Puisi visual Erna memperlihatkan bagaimana bahasa mengadopsi kualitas spasial seni rupa dengan mewujudkan imaji sebagai bentuk, bukan sekadar makna verbal.
Puisi dan seni rupa sebenarnya seperti dua saudara yang lahir dari ibu yang sama yaitu imajinasi. Puisi berbicara lewat kata, seni rupa lewat garis, warna, dan bidang. Tapi keduanya sama-sama berusaha melakukan hal yang mirip yaitu menangkap sesuatu yang tak kasat mata, lalu memberinya bentuk agar bisa disentuh perasaan manusia.
Ketika kita membaca puisi yang kuat, sering kali yang muncul lebih dulu justru gambar di kepala, bukan makna harfiahnya. Sebuah larik tentang “langit retak oleh senja” segera menghadirkan warna, cahaya, bahkan suhu. Itu sebabnya banyak penyair sesungguhnya adalah pelukis yang bekerja dengan bahasa. Sebaliknya, pelukis sering disebut penyair yang memilih diam, membiarkan warna berbicara menggantikan kata.
Hubungan ini bukan hal baru. Dalam tradisi dunia, kita mengenal William Blake, penyair sekaligus perupa Inggris, yang menulis puisi dan menggambarnya sendiri dalam satu lembar visual-puitik. Puisinya tidak bisa dipisahkan dari ilustrasinya di mana kata dan rupa menyatu sebagai pengalaman utuh. Di Indonesia kita bisa mengingat sosok seperti Affandi yang lukisannya sering disebut “penuh puisi” karena sapuan garisnya seolah menjeritkan emosi, atau penyair-penyair yang juga melukis dan membuat karya visual, menjadikan kanvas sebagai halaman lain dari buku batin mereka.
Secara teori, hubungan ini bisa dibaca lewat gagasan intermedialitas yaitu pertemuan dan dialog antar medium seni. Puisi memberi waktu, seni rupa memberi ruang. Puisi mengalir sekuensial, larik demi larik, sementara lukisan hadir sekaligus dalam satu tatapan. Namun keduanya bertemu di wilayah yang sama, yaitu menggugah. Hanya saja menggugah dalam puisi adalah “lukisan dengan kata”, sedangkan lukisan adalah “puisi yang dibekukan dalam bentuk”.
Bagi saya pribadi, setiap kali melihat lukisan yang kuat, saya selalu merasa seperti sedang membaca puisi tanpa huruf. Ada getaran yang sulit dijelaskan, semacam rasa yang datang lebih dulu sebelum pikiran sempat memberi nama. Sebaliknya, ketika membaca puisi yang menyentuh, sering kali saya seperti sedang berdiri di depan kanvas besar di dalam diri, penuh warna-warna kenangan, cahaya masa lalu, bayangan luka, semuanya muncul pelan-pelan.
Mungkin karena itu, ketika puisi dan seni rupa bertemu dalam diri seorang seniman seperti Erna Winarsih Wiyono, yang lahir bukan sekadar karya, tetapi ruang batin yang lebih luas. Kata memperdalam makna gambar, gambar memperkaya rasa kata. Dan di pertemuan itu, kita sebagai penikmat tidak hanya membaca atau melihat, melainkan kita ikut merasakan, seolah diberi kesempatan menyentuh isi hati manusia lain dengan cara yang paling halus.
SPIRITUALITAS EKSISTENSIAL
Pendekatan spiritualitas personal ini dapat dikaitkan dengan pemikiran Viktor Frankl dalam logoterapi, yang melihat makna hidup sering ditemukan justru dalam penderitaan. Juga dekat dengan gagasan Paul Tillich tentang “ultimate concern”, yakni pengalaman religius sebagai relasi eksistensial, bukan hanya dogma.
Spiritualitas dalam buku ini pun terasa intim. Tuhan hadir bukan sebagai konsep besar yang menggurui, tetapi sebagai tempat bersandar ketika napas terasa berat. Doa muncul dalam sunyi, dalam malam, dalam kelelahan. Ini mendekati apa yang disebut spiritualitas eksistensial, ketika relasi dengan Yang Ilahi tumbuh dari pengalaman personal, bukan semata aturan luar. Nada pasrah yang muncul bukan berarti menyerah, melainkan menerima dengan kesadaran penuh. Di situ ada ketenangan yang matang.
RUANG DISKUSI TERHADAP BUKU INI
Secara sastra, kelugasan bahasa memang membuat puisi-puisi ini mudah dipahami, tetapi kadang mengurangi lapisan ambiguitas yang biasanya memberi ruang tafsir lebih luas. Namun saya merasa ini adalah pilihan estetik yang sadar. Penyair tampaknya lebih memilih kejujuran emosi daripada kerumitan simbol. Ia ingin dekat dengan pembaca, bukan memancing jarak.
Ada satu anggapan lama dalam dunia puisi di mana semakin sulit puisi dipahami, makin “tinggi” nilainya. Seolah-olah kabut adalah tanda kedalaman, dan kejernihan justru dicurigai sebagai kesederhanaan yang dangkal. Tapi setiap kali saya berhadapan dengan puisi-puisi yang lahir dari pengalaman hidup yang sungguh-sungguh dijalani seperti sakit, kehilangan, tubuh yang menua, bumi yang terluka, doa yang lirih, semua anggapan itu selalu terasa goyah.
Kelugasan bahasa sering dianggap mengurangi ambiguitas. Betul. Tapi pertanyaannya: apakah setiap puisi memang harus menjadi labirin tafsir yang sulit dan rumit?
Dalam tradisi puisi modern, ambiguitas memang dipuja. Makna yang bercabang, simbol yang berlapis, metafora yang membuka banyak pintu, semua itu membuat puisi seperti ruang gema. Sekali dibaca, belum selesai. Dua kali dibaca, masih menyimpan rahasia. Di situ ada kenikmatan intelektual di mana pembaca merasa diajak berburu makna, menafsir, meraba-raba cahaya dalam gelap.
Namun ada jenis puisi lain yang tidak berdiri di wilayah itu. Puisi yang tidak ingin menjadi teka-teki, tetapi ingin menjadi tangan yang menyentuh pelan bahu kita. Puisi yang tidak berkata, “Pahami aku,” melainkan secara lugas mengajak, “Duduklah di sini sebentar.”
Di sinilah kelugasan bahasa mengambil peran yang berbeda. Ia bukan tanda kemiskinan imajinasi, melainkan pilihan sikap. Bahasa yang jernih membuat pembaca tidak tersandung di pintu masuk. Ia tidak sibuk bertanya, “Apa maksudnya?”, tetapi langsung sampai pada pertanyaan yang lebih dalam, “Mengapa ini terasa begitu dekat dengan saya?”
Puisi yang lugas cenderung bekerja lewat empati, bukan enigma. Ia tidak memamerkan kerumitan, tetapi membuka kehadiran. Menurut saya, puisi-puisi yang lahir dari pengalaman genting hidup, kehadiran sering lebih penting daripada misteri.
Bayangkan seseorang yang menulis dari ruang sakit, dari kelelahan batin, dari kegelisahan melihat bumi rusak, atau dari sunyi doa di malam hari. Dalam situasi seperti itu, bahasa sering kehilangan keinginan untuk bersembunyi di balik simbol-simbol rumit. Ia ingin langsung mampir seperti kesaksian, seperti seseorang yang berkata, “Ini yang saya rasakan,” bukan “Coba tebak apa yang saya sembunyikan.”
Memang, ketika ambiguitas berkurang, ruang tafsir yang liar juga menyempit. Puisi tidak lagi berkilau sebagai teka-teki eksistensial yang bisa dibedah berkali-kali. Tapi sebagai gantinya, ia menghadirkan sesuatu yang lain, yaiu keintiman. Kita tidak berdiri sebagai penafsir di luar teks, melainkan sebagai sesama manusia yang duduk berhadapan.
Di situ puisi berubah fungsi. Ia tidak lagi terutama menjadi medan permainan makna, melainkan ruang pertemuan pengalaman. Kita tidak merasa sedang membaca karya sastra yang ingin dikagumi dari kejauhan, tetapi suara seseorang yang sedang mencoba bertahan hidup dan mengajak kita ikut bernapas bersamanya.
Mungkin memang ada puisi yang perlu menjadi kabut, agar kita belajar melihat dalam samar. Tapi ada juga puisi yang perlu menjadi udara jernih, agar kita bisa bernapas lega setelah lama sesak.
Kelugasan bahasa, dalam konteks seperti itu, bukan kekurangan. Ia adalah keberanian untuk tidak bersembunyi. Dan kadang-kadang, di dunia yang sudah terlalu penuh dengan kebisingan simbol dan permainan citra, kejujuran yang sederhana justru terasa paling puitik.
Setelah menutup buku ini, saya tidak merasa selesai membaca karya sastra dalam pengertian akademis. Saya merasa seperti baru saja menemani seseorang yang bernama Erna Winarsih Wiyono melewati banyak musim hidup. Buku ini menunjukkan bahwa puisi bisa menjadi ruang terapi, dialog dengan bumi, suara perempuan, dan doa sunyi sekaligus. Ia membuktikan bahwa sastra tidak selalu harus berdiri megah di panggung teori, kadang ia cukup menjadi bangku kayu di stasiun kecil, tempat kita duduk sebentar, menata napas, sebelum melanjutkan perjalanan.
Menurut saya mungkin di situlah makna terdalamnya. Ketika hidup terasa sesak, ketika dunia terlalu bising, puisi bisa menjadi napas cadangan. Sebuah tempat pulang yang sederhana, tetapi cukup untuk membuat kita bertahan tetap menjalani hidup.
Cibubur, Februari 2026
Riri Satria lahir di Padang, Sumatra Barat, 14 Mei 1970, adalah seorang akadeisi serta pelaku dunia bisnis di bidang teknologi dan transformasi digital, serta pencinta sastra, saat ini sebagai Ketua Jagat Sastra Milenia (JSM).
Puisinya telah diterbitkan dalam beberapa buku kumpulan puisi tunggal: “Jendela” (2016), “Winter in Paris” (2017), “Siluet, Senja, dan Jingga” (2019), “Metaverse” (2022), “Algoritma Kesunyian” (2023, bersama penyair Emi Suy), “Login Haramain” (2025), serta lebih dari 80 buku kumpulan puisi bersama.
Riri juga menulis esai dan telah diterbitkan dalam beberapa buku: “Untuk Eksekutif Muda” (2003), trilogi “Proposisi Teman Ngopi” (2021) yang terdiri tiga buku “Ekonomi, Bisnis, dan Era Digital”, “Pendidikan dan Pengembangan Diri”, dan “Sastra dan Masa Depan Puisi”; serta kumpulan esai sastra “Jelajah” (2022).
Saat ini Riri adalah Komisaris Utama PT. ILCS Pelindo Solusi Digital, sebuah perusahaan teknologi digital dalam grup Pelabuhan Indonesia (Pelindo); Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia; Anggota Dewan Pertimbangan Ikatan Alumni Universitas Indonesia; serta Juri atau Kurator Indonesia Digital Culture Excellence Award dan Indonesia Human Capital Excellence for Resilience Award. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menko Polkam RI Bidang Transformasi Digital dan Keamanan Siber (2024 – 2025), serta Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (2011-2018).
Facebook: www.facebook.com/ririsatria.va2
Instagram: www.instagram.com/riri.sat.ria
Website: www.ririsatria.id
Riri Satria
Riri Satria lahir di Padang, Sumatera Barat 14 Mei 1970, aktif bergiat di dunia kesusastraan Indonesia, pendiri serta Ketua Jagat Sastra Milenia (JSM) di Jakarta, serta menulis puisi. Namanya tercantum dalam buku “Apa dan Siapa Penyair Indonesia’ yang diterbitkan Yayasan Hari Puisi Indonesia (2018). Puisinya sudah diterbitkan dalam buku puisi tunggal: “Jendela” (2016), “Winter in Paris” (2017), “Siluet, Senja, dan Jingga” (2019), “Metaverse” (2022), serta "Login Haramain" (2025), di samping lebih dari 60 buku kumpulan puisi bersama penyair lainnya, termasuk buku kumpulan puisi duet bersama penyair Emi Suy berjudul “Algoritma Kesunyian” (2023).
Riri juga menulis esai dengan beragam topik: sains dan matematika, teknologi dan transformasi digital, ekonomi dan bisnis, pendidikan dan penelitian, yang dibukukan dalam beberapa buku: “Untuk Eksekutif Muda: Paradigma Baru dalam Perubahan Lingkungan Bisnis” (2003), trilogi “Proposisi Teman Ngopi” (2021) yang terdiri tiga buku “Ekonomi, Bisnis, dan Era Digital”, “Pendidikan dan Pengembangan Diri”, dan “Sastra dan Masa Depan Puisi” (2021), serta “Jelajah” (2022). Diperkirakan buku kumpulan esai terbaruya tentang kesusastraan, kesenian, kebudayaan, serta kemanusiaan akan terbit pada tahun 2026.
Dalam beberapa tahun terakhir ini sejak tahun 2018, Riri Satria aktif menekuni dampak teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) atau AI) terhadap dunia kesusastraan, terutama puisi. Riri diundang menjadi narasumber untuk membahas topik ini di berbagai acara sastra, antara lain: Seminar Internasional Sastra di Universitas Pakuan, Bogor (2018), Seminar Perayaan Hari Puisi Indonesia, Jakarta (2019), Banjarbaru’s Rainy Day Literary Festival, Banjarbaru Kalimantan Selatan (2019), Seminar Perayaan Hari Puisi Indonesia, Jakarta (2021), Malay Writers and Cultural Festival (MWCF) 2024 di Jambi (2024), Seminar Jambore Sastra Asia Tenggara (JSAT) di Banyuwangi (2024), Seminar Etika Kreasi di Era Digital, Diskusi Hak Cipta dan Filosofi AI yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta (2025), serta memberikan kuliah umum tentang topik pada Pertemuan Penyair Nusantara XIII (2025) di Perpustakaan Nasional RI.
Saat ini Riri Satria menjabat sebagai Komisaris Utama PT. ILCS Pelindo Solusi Digital PSD sejak April 2024, sebuah perusahaan teknologi dalam grup Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Sebelumnya selama 5 tahun Riri menjabat sebagai Komisaris Independen pada PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) 2019-2024, sebuah pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia yag merupakan joint venture antara Pelabuhan Indonesia dengan Hutchison Port Holdings Hongkong melalui Hutchison Ports Indonesia.
Riri juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Meko Polkam RI) bidang Digital, Siber, dan Ekonomi sejak Oktober 2024 s/d September 2025,
Riri juga anggota Dewan Juri untuk Indonesia Digital Culture Excellence Award serta Indonesia Human Capital Excellence Award sejak tahun 2021. Riri juga dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, dan mengajar topik Sistem Korporat, Bisnis Digital, Manajemen Strategis Sistem Informasi, serta Metodologi Penelitian untuk program Magister Teknologi Informasi (MTI). Selain itu Riri adalah Anggota Dewan Pertimbangan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan sebelumnya Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.
Berita Terkait
Konten Populer
Pada tahun 2025, transaksi ekonomi digital diperkirakan se besar Rp 1.775 T. Ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan terus berkembang dengan nilai transaksi diprediksi akan mencapai US$124 miliar atau sekitar Rp1.775 triliun pada tahun 2025. Dengan proyeksi tersebut, Indonesia akan berada pada peringkat pertama di ASEAN sebagai negara dengan nilai transaksi ekonomi digital terbesar dengan kontribusi […]
Jul 02, 2025Mengawali tulisan ini, saya ingin mengucapkan alhamdulillah puji syukur kepada Allah Jalla wa Alaa atas segala karunia di setiap detik dan hela napas pada hamba-hamba-Nya. Saya mengucapkan selamat serta ikut bangga dan bahagia atas amanah baru yang diembankan negara kepada Ketua Komunitas Jagat Sastra Milenia (JSM), abang, sahabat, penyair, sang inspirator Riri Satria sebagai Komisaris Utama […]
Apr 13, 2024Era digital ini dengan segala kemajuannya seperti kecerdasan buatan, metaverse, bahkan media sosial sederhana pun seperti Facebook ini memiliki potensi dahsyat untuk melakukan rekayasa terhadap persepsi atau perception engineering. Ya, sekarang eranya post truth society dan dunia penuh dengan yang namanya perseption engineering. Saat ini, perception is the reality, walaupun mereka yang sanggup berpikir […]
May 27, 2024oleh: Riri Satria Hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2024. Kita memperingatinya saat ini dengan meresmikan Digital Maritime Development Center (DMDC) PT. Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) / Pelindo Solusi Digital (PSD), yang sama-sama kita banggakan. Ini adalah pusat penelitian, pengembangan, dan inovasi solusi digital terintegrasi untuk ekosistem logistik maritim di Indonesia. […]
May 20, 2024Riri Satria adalah seorang pengamat ekonomi digital dan kreatif, sekaligus pencinta puisi yang lahir di Padang, Sumatera Barat, 14 Mei 1970. Sarjana Ilmu Komputer (S. Kom) dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia yang mengambil Magister Manajemen (MM) dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM ini tengah menempuh program S3 Doctor of Business Administration (DBA) di Paris School […]
Nov 14, 2021MENJAWAB TANTANGAN, MENJEMPUT MASA DEPAN SASTRA KOTA Ketika UNESCO menetapkan Jakarta sebagai City of Literature pada tahun 2021, banyak dari kita yang bersorak—dengan bangga, tentu saja. Sebuah pengakuan internasional untuk kota yang sibuk, padat, dan penuh riuh—tapi ternyata juga menyimpan denyut sastra yang tak pernah mati. Namun bersamaan dengan sorak itu, sebuah pertanyaan segera […]
May 17, 2025Assalamu alaikum wr wb. Salam dari Arafah, Mekkah Al Mukarramah. Tahukah sahabat bahwa nama Sukarno sangat terkenal di Arafah? Ya, pohon yang di belakang saya itu disebut oleh orang sini sebagai Pohon Sukarno. Pohon Soekarno di Padang Arafah adalah warisan hijau yang berasal dari usulan Presiden Sukarno saat melaksanakan ibadah haji pada tahun 1955. Usulan […]
May 27, 2025Mungkinkah seseorang mengeluti 3 profesi sekaligus secara serius dan sepenuh hati?. Bisa. Inilah yang dilakukan oleh Riri Satria, Sang Polymath Di suatu siang, Riri memasuki pelataran Taman Ismail Marzuki (TIM) dengan santai. Berkaos oblong, bercelana jeans serta beralas sandal. Di perjalanan memasuki sebuah ruang sastra, ia bertegur sapa dengan sejumlah seniman yang sedang berkumpul. Tanpa […]
Jun 06, 2021
RECENT EVENT
Riri Satria tentang Bencana Alam Sumatera
NEXT EVENT
POJOK PODCAST